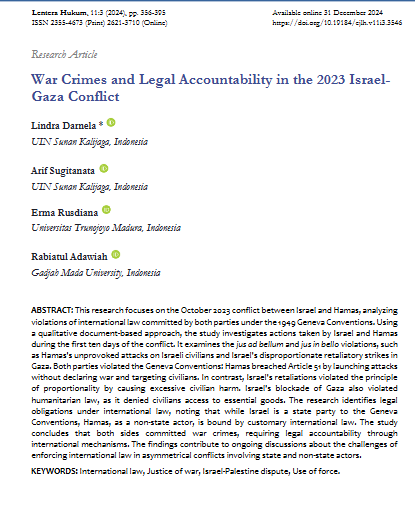Review Terhadap Artikel: War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict
Oleh: Fajri Matahati Muhammadin
Pada tanggal 31 Desember 2024 tahun lalu, telah terbit sebuah artikel berjudul “War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict” yang ditulis oleh Ibu Dr. Lindra Darnela dari UIN Sunan Kalijaga, yang juga saat itu masih menjabat sebagai Ketua di INSANIA, beserta rekan-rekannya yaitu Arif Sugitanata, Erma Rusdiana, dan Rabiatul Adawiyah.
Dalam post ini saya akan memberikan ulasan kritis internal (sebagai sesama pengurus INSANIA) terkait beberapa poin yang dibawakan. Tapi, sebagai permulaan, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, sayangnya terbitnya sudah 31 Desember 2024. Padahal selang beberapa pekan, sudah bisa diberi judul “2023-2025 israel-Gaza conflict”. Alhamdulillah sudah ada gencatan senjata, meskipun pertempuran bergeser ke Tepi Barat. Kedua, saya senang INSANIA ada yang mengangkat tema ini karena meskipun saya bukan orang Palestina tapi Gaza sangat dekat di hati saya, dan juga dekat sekali dengan objek kajian INSANIA.
Baik, berikut beberapa ulasan kritis dari saya.
Poin Pertama: Pelanggaran “Jus Ad Bellum”
Ada beberapa hal yang sangat perlu saya soroti terkait apa yang diklaim sebagai pelanggaran “jus ad bellum”.
- Status “non-state actor” yang disematkan kepada HAMAS (hlm 360 dan halaman-halaman lainnya) sangat perlu dievaluasi karena akan berdampak hukum dalam banyak hal. Padahal, sebenarnya perlu dikaji lagi basic hukum internasionalnya khususnya pada atribusi perbuatan kepada negara (ILC Articles on the Responsibility of State). Catat bahwa HAMAS adalah partai politik pemenang pemilu dan pemegang pemerintahan di Gaza (memiliki otonomi juga dalam pemerintahan Palestina), dan Kata’ib Al-Qassam adalah sayap militer Hamas. Sebagai bandingan, di Republik Rakyat Cina juga itu Partai Komunis adalah penguasa di sana dan tentara mereka (People’s Liberation Army) itu adalah sayap militer parpol lho. Tapi, meskipun penulis menyebut bahwa Hamas berkuasa di wilayah Gaza tapi tidak berfikir sampai pada dampaknya terhadap hukum internasional. Mereka menetapkan sendiri bahwa Hamas adalah “non-state actor”, maka kita lihat konsekuensinya apa.
- Salah satunya, adalah apakah HAMAS bisa dikatakan melakukan “agresi” dari sudut pandang subjek? Menurut definisi Act of Aggression (Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314[XXIX] tahun 1974), salah satu unsur “agresi” adalah “…the use of armed force by a State.” Ini lebih dipertegas lagi di Pasal 8bis (1) dan (2) Rome Statute 1998. Jadi, kalau misalnya penulis bersikeras bahwa HAMAS disebut sebagai non-state actor, tapi kemudian di halaman 368 dst penulis juga menyalahkan Hamas atas “agresi”, ini merupakan kekeliruan besar.
- Masalah tidak berhenti sampai sana. Definisi “agresi” juga memiliki unsur “against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State”. Mungkin penulis harus memeriksa Kembali, wilayah mana yang diserang oleh Hamas dan apa statusnya dalam hukum internasional. Apakah Occupied Territories (yang oleh hukum internasional diakui sebagai bukan milik sah israel bahkan oleh mayoritas negara yang mengakui israel, ditegaskan di Resolusi Majelis Umum PBB, juga ICJ Advisory Opinion terbaru tahun 2024 lalu)? Ataukah Penulis bermaksud mengakui bahwa seluruh wilayah tersebut memang sah milik israel?
- Masalah masih juga tidak berhenti sampai di situ. Penulis menyebut di halaman 369 bahwa pada tanggal 7 Oktober Hamas melakukan “unprovoked attack”, dan di halaman 371 disebut “without legitimate grounds for self-defense”. Ini seperti ada sinetron 10 season, tapi baru menonton mulai season 9. Penjajahan terhadap bangsa Palestina sudah berjalan sejak tahun 1940an dan terus berkesinambungan sampai dengan hari ini, ada saja berita serangan baik ke wilayah Gaza ataupun Tepi Barat atau di Jerusalem, dari zaman orangtua saya masih balita sampai saya sudah berusia jelang 40 ya seperti itu. Tidak selalu terjadi eskalasi besar seperti konflik tahun 2023 (meskipun tidak jarang juga), tapi tidak pernah absen. Lalu tiba-tiba Hamas menyerang balik dibilang “unprovoked” ini ceritanya bagaimana ya? Ini adalah apa yang dapat disebut sebagai: a very classical case of self defense. Tapi, tentu tidak akan terlihat seperti itu kalau kita tidak mengikuti konfliknya dari awal.
- Masalah masih ada juga, karena di halaman 370 disebut bahwa serangan 7 Oktober disebut melanggar Jus Ad Bellum karena “no declaration of war”. Pertama, sejak kapan deklarasi menjadi syarat keabsahan sebuah perang? Mungkin penting menyertakan dasar hukumnya, karena saya baru tahu. Kedua, ini bukti tambahan bahwa penulis belum mengikuti konflik dari awal, karena perang sudah terjadi sejak lama sekali. Masa setiap menyerang harus memberikan warning dulu? Dalam konteks perang sudah terjadi, berarti masuk ke HHI. Pasal 57(2)(c) Additional Protocol I tahun 1977 menyatakan bahwa kewajiban memberikan warning adalah tergantung kondisi, dan ICRC menjelaskan lebih lanjut dalam buku Customary International Humanitarian Law (Haenckarts and Doswald-Beck) bahwa “kondisi” ini adalah urgensi elemen kejutan dalam operasi militer tersebut. Kita ketahui bahwa suksesnya operasi militer Hamas, dan mayoritas operasi militer pihak yang lemah dalam perang asimetris, pastinya sering bergantung pada elemen kejutan.
- Masih belum selesai masalahnya, karena dikatakan bahwa “israel’s actions may be considered under the law of war (jus ad bellum)” di halaman 383. Ini juga perpanjangan masalah penulis yang tidak menganalisis perang ini dari awal, dan seakan menganggap sebelum 7 Oktober 2023 semua baik-baik saja damai Sentosa dengan burung-burung berkicau riang dan ikan melompat-lompat bahagia. Bagaimana bisa dikatakan bahwa serangan oleh israel sebagai penjajah kepada jajahannya bersifat sah menurut jus ad bellum? Lagi, seakan ini serangan pertama dan belum ada perang sebelumnya.
Poin kedua: Pelanggaran “Jus In Bello”
Terkait hukum humaniter internasional, berikut beberapa poin catatan dari saya:
- Ini turunan masalah klasifikasi Hamas sebagai non-state actor, sebagaimana di Poin Pertama butir (1), tapi dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penulis menyebut bahwa non-state actor tetap terikat Hukum Humaniter Internasional, dan ini tentu saja benar. Tapi, itu dalam konteksnya adalah dalam non-international armed conflict sebagaimana di Additional Protocol II tahun 1977. Apakah tim penulis menganggap perang Gaza ini adalah non-international armed conflict antara israel sebagai pemerintah yang sah melawan Hamas sebagai non-state actor di dalam negara israel (berarti, mengakui kedaulatan israel atas Gaza)?
- Padahal jelas ini international armed conflict, karena merupakan perang melawan kekuatan kolonial dan rezim rasis. Ini adalah sub-varian international armed conflict dalam Additional Protocol I tahun 1977 yang tidak mensyaratkan dua (atau lebih) negara sebagai pihak dalam perangnya. Maka kalau penulis bersikeras bahwa Hamas adalah non-state actor, apa ya dasar hukum untuk menyatakan bahwa Hamas terikat HHI?
- Di Halaman 370-371, penulis lebih merinci lagi apa yang dianggap sebagai war crimes yang dilakukan oleh HAMAS. Akan tetapi, nampaknya penulis belum mengkaji lebih lanjut tentang insiden-insiden ini. Perlu diingat bahwa banyak sekali di antara korban pada serangan ke Supernova dan lainnya (FYI, 260 korban di Supernova termasuk dalam 1100 korban total yang dilaporkan, kok ditulis terpisah ya?) dan penyanderaan adalah anggota aktif IDF. Tentu mereka kombatan, apalagi yang bukan anggota aktif IDF pun banyak yang merupakan reservist (tentara cadangan). Ini tentu tidak menafikan bahwa ada yang non-kombatan di antara mereka, tapi skala (Bahasa hukumnya gravity of crimes) sangat relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana nantinya. Belum lagi, penulis belum mempertimbangkan “Hannibal directive” yang dilakukan oleh IDF yang saat itu akhirnya menembak rakyatnya sendiri demi menghentikan serangan Hamas. Bahkan banyak beredar footage pasukan Hamas yang melindungi warga israel dari tembakan IDF sendiri.
- Khusus poin “indiscriminate attacks”, nampaknya penulis kurang mengkaji sumber hukum dan kondisi faktual dengan rinci yang relevan dengan indiscriminate attacks dan “gandengannya” yaitu principle of proportionality. Indiscriminate attacks ini analisisnya sangat tergantung kondisi dan multifaktor. Yang banyak dipermasalahkan adalah ketidakakuratan roket-roket ini, sehingga diklaim bersifat indiscriminate. Akan tetapi, belum dipertimbangkan bahwa Hamas tidak punya senjata lain yang lebih akurat untuk menyasar pasukan israel yang lebih jauh. Apakah dengan dalih HHI ini berarti pihak yang terjajah hanya boleh melawan kalau dia cukup kaya dan punya senjata bagus, dan kalau miskin tidak boleh melawan penjajahnya? Kondisi perang asimetris sangat berdampak pada cara kita menganalisis perang, khususnya indiscriminate attacks. Pertimbangan perang asimetris akan masuk ke dalam kalkulasi prinsip proporsionalitas dan hukum-hukum rinci terkait reprisals (misalnya, banyak dirinci di kasus ICTY Prosec v. Kupreskic, Trial Judgment). Lagipula, berapa besar juga sih daya ledaknya roket-roket Hamas ini dan korban-korbannya? Nggak seberapa juga. Masa tidak diperhitungkan?
- Poin yang menarik tapi belum dibahas adalah terkait tawanan dan sandera. Pihak israel banyak sekali terdokumentasi memperlakukan tawanan Palestina dengan tidak manusiawi dalam perang ini (dan juga dari jauh sebelumnya sih, cuma nampaknya Penulis kan tidak melihat konflik ini dari awal xixixi), termasuk menjadikan mereka sebagai human shield. Bahkan, pertanyaan hukum juga, banyak kasus israel membunuh tawanan israel sendiri yang ditawan oleh Hamas. Ada yang “tidak sengaja” (meskipun sangat sembrono, issue proportionality nih), ada juga yang nampak sengaja. Padahal, banyak tawanan ini yang juga anggota IDF. Apakah melanggar HHI kalau membunuh pasukan sendiri yang sedang ditawan oleh pihak lawan? Pertanyaan menarik.
- Penasaran juga, dugaan pelanggaran Hamas sampai dibuatkan table biar cantik, tapi kenapa yang israel tidak dibuatkan.
Justifikasi kepada kedua belah pihak dari dukungan israel
Halaman 380 dst membahas kemungkinan legitimasi atas perbuatan para pihak dalam perang Gaza, khususnya dari perspektif dukungan komunitas internasional. Ada beberapa catatan saya:
- Dukungan dari berbagai pihak kepada israel betul memberi legitimasi atas serangan israel dari sudut jus ad bellum, menganggapnya sebagai self defense melawan serangan oleh Hamas. Yang penting untuk kita kaji adalah udang apa yang ada di balik bakwan ini. Jawabanya, adalah pengakuan terhadap pendudukan israel atas wilayah jajahan. Dengan udang seperti ini, bakwannya berwujud sebagai berikut: jika pihak yang menyerang dibilang melanggar hukum, dan yang diserang memiliki hak self defense. Kok persis seperti stance penulis ya? Nah lho.
- Yang kurang dibahas adalah betapa banyaknya negara yang mendukung israel secara jus ad bellum, tapi mengkritik dengan sangat keras terkait jus in bello-nya sehingga turut menekan ceasefire. Bahkan angka negara yang sangat banyak mendukung Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2024 yang memerintahkan pemukim israel untuk hengkang dari wilayah jajahan, jangan-jangan ada negara yang berubah stance terkait legitimasi israel secara jus ad bellum. Pembahasan oleh penulis belum sampai ke sini.
- Analisis terkait legitimasi operasi militer Hamas dari sudut “state response” sebenarnya dapat diperkuat lagi dengan masalah perang asimetrik. HHI masih agak berat dalam merespon kondisi perang yang asimetrik, apalagi yang asimetrinya separah dan se-jomplang israel-Palestina.
Analisis terkait “Aftermath of the Hamas-israel War”
Sekali lagi, naskah ini terbit sebelum sempat menyaksikan gencatan senjata permanen. Akan tetapi, di sini ada beberapa catatan.
- Saya menantikan analisis terkait poin-poin penting yang harus dilakukan oleh para pihak dan masyarakat internasional ketika perang sudah berakhir, khususnya dalam konteks pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang dituduhkan. Terutama karena artikel ini berjudul “… and legal accountability”. Tentu setidaknya sebagai spekulasi karena artikel ditulis sebelum gencatan senjata. Akan tetapi, bab ini hanya mengulang bahwa “para pihak harusnya tidak melakukan pelanggaran hukum”, tapi lalu “aftermath”nya mana? Apa akuntabilitas yang mau dibahas?
- Ketika ICJ disebut-sebut, saya berharap melihat analisis putusan ICJ baik dalam kasus Afrika Selatan vs israel (memberikan kewajiban untuk persiapan investigasi kejahatan genosida) atau Advisory Opinion (memerintahkan pemukim israel pergi dari wilayah terokupasi), keduanya tahun 2024. Krusial sekali dalam perkembangan konflik Gaza, apalagi kalau mau bahas akuntabilitas. Yah, tapi malah nggak dibahas.
- Terkejut sekali ketika ICC juga tidak dibahas sama sekali. Padahal Arrest Warrant sudah dikeluarkan untuk petinggi israel maupun Hamas. Masa ini bukan poin penting terkait “akuntabilitas” dan “justice in the aftermath”? Apalagi, dari perspektif Hamas, tiga nama yang masuk Arrest Warrant (Ismail Haniyyah, Yahya Sinwar, dan Muhammad Dheif) semuanya sudah meninggal. Haniyyah dan Sinwar sudah diketahui meninggal sekitar pertengahan tahun 2024, sedangkan Muhammad Dheif sudah berkali-kali diklaim oleh israel telah terbunuh termasuk di tahun 2024 (tapi israel juga apresiasi ada arrest warrant untuk Dheif, lucu juga), tapi baru dikonfirmasi oleh Hamas di tahun 2025 ini beberapa hari yang lalu.
- Belum lagi, ada beberapa negara yang sudah mengklaim siap menangkap Netanyahu dan Gallant kalau berkunjung ke negara mereka, bahkan sudah ada negara yang siap (atau bahkan telah) menahan anggota IDF dengan tuntutan genosida.
- Belum lagi bicara tentang keadilan restoratif terkait korban-korban perang, yaitu pemulihan baik dari segi nyawa maupun materi dan infrastruktur Gaza yang porak poranda ini. Sudah sejak tahun lalu ada berbagai negara dan organisasi internasional yang sudah menyatakan siap untuk membantu membangun Kembali Gaza pasca perang, tapi sekali lagi ini tidak dibahas.
Demikian ulasan ini saya buat, dengan niat sebagai masukan konstruktif dan bisa dijadikan bahan untuk penelitian-penelitian lain ke depan.