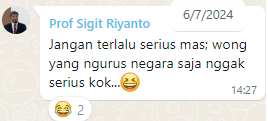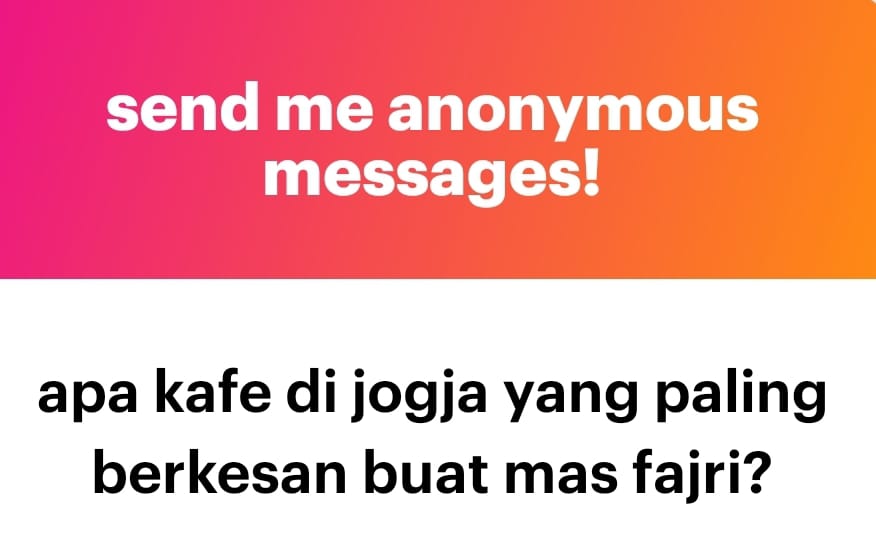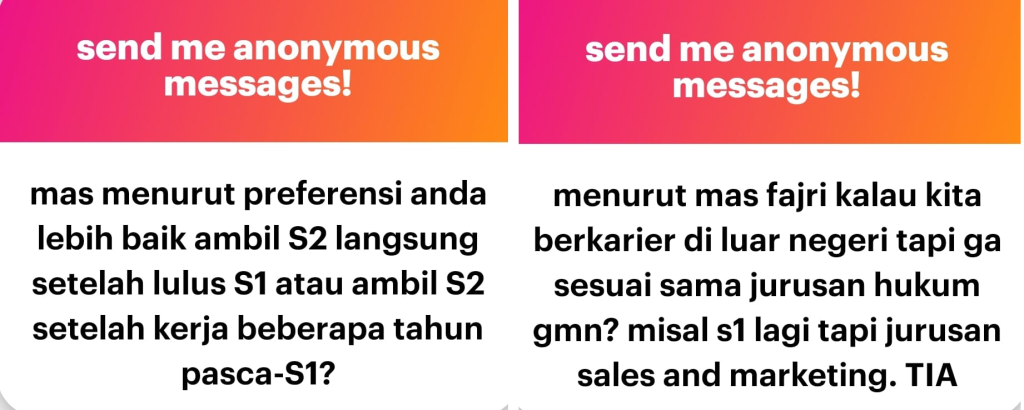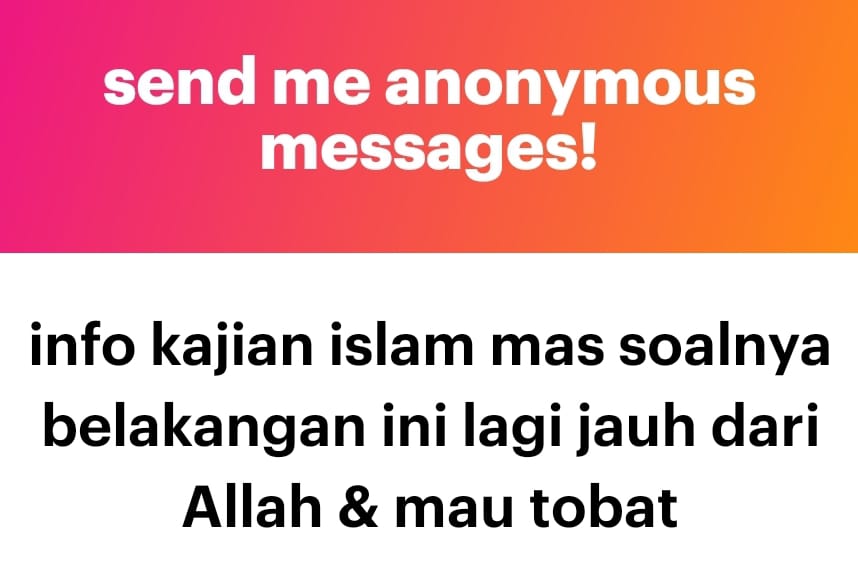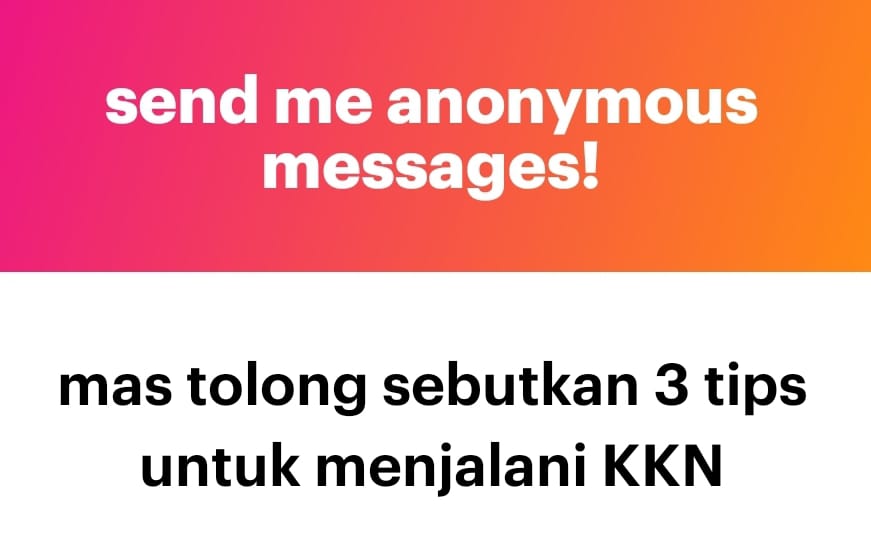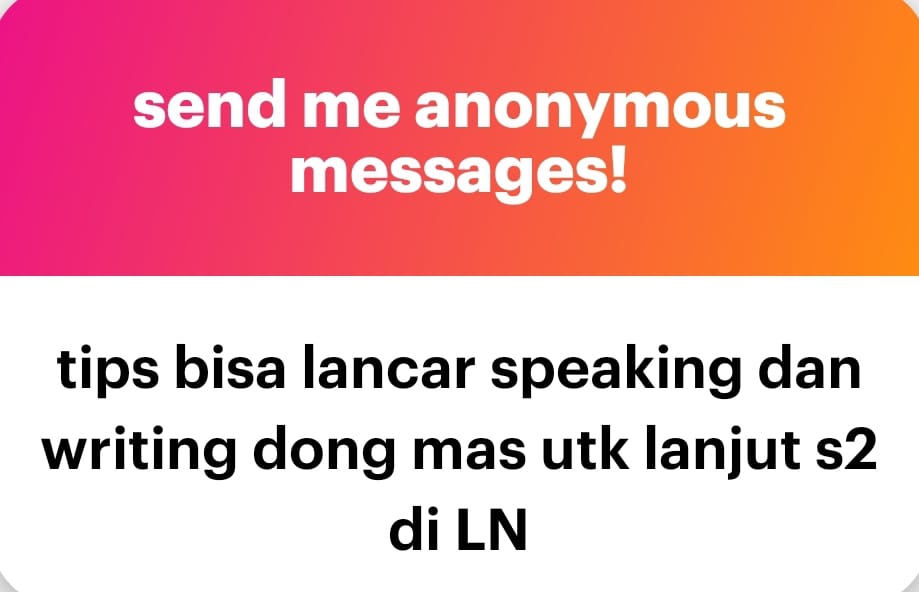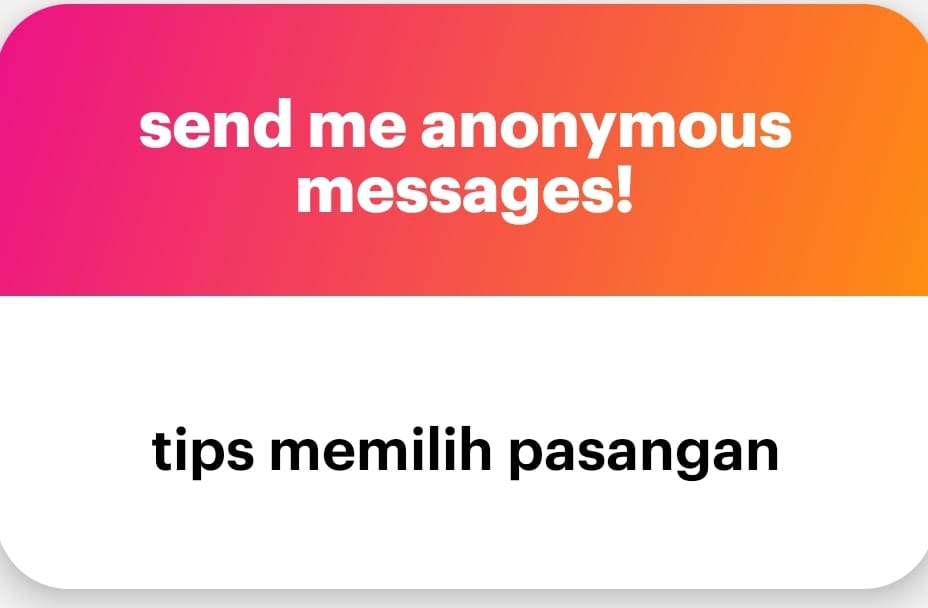Home » 2024
Yearly Archives: 2024
Prof. Dr. Sigit Riyanto: Sebuah Obituari
Baru lusa kemarin, seperti biasanya, saya beberapa kali berpapasan dengan beliau di kantor (ruangan kami satu lantai selisih beberapa pintu saja) dan sesekali obrolan kami mengandung cekakak cekikik. Kemarin pagi kami terjadwal untuk menjadi panelis siding thesis magister untuk ujian bimbingan beliau. Jam 3 dinihari beliau dilarikan ke UGD, tapi sidang tidak dibatalkan melainkan hanya dijadikan hybrid (khusus beliau hadir secara online, peserta dan penguji lain hadir secara offline).
Menjelang sidang dimulai, seperti biasa kami basa basi sedikit dengan beliau yang tidak mengaktifkan kamera tapi melalui mikrofon beliau menanggapi. Kemudian beliau berkata, “Monggo Pak Harry, silahkan dimulai” pada Pak Dr. Harry Purwanto yang menjadi ketua sidang, dan itulah terakhir saya mendengar suara beliau. Di tengah persidangan, beliau mengirimkan pesan WhatsApp menyampaikan bahwa beliau tidak perlu mengajukan pertanyaan. Toh mahasiswa ini bimbingan beliau yang tentunya sudah berproses panjang. Saya meng-oke-kan, lalu mendoakan beliau cepat sembuh. Tanggapan beliau hanya emoji: 🙏🙏🙏, dan itulah pesan terakhir yang saya terima dari beliau.
Pagi ini, setelah shalat subuh dan mulai memasak untuk sarapan anak saya, datang kabar wafatnya beliau. Yang pertama muncul di benak saya: who else can I look up to, now? (maksudnya di kampus). Alhamdulillah istri saya berbaik hati menawarkan untuk mengantar anak saya sekolah (saat itu anak saya baru mulai makan, belum mandi), supaya saya bisa menyusul ke Rumah Sakit Akademik UGM untuk menemui Prof Sigit untuk terakhir kalinya.
Di perjalanan, sambil mengemudi sepeda motor, belasan tahun saya kenal dengan Prof Sigit terputar dalam kilasan-kilasan di benak saya.
Beliau adalah “guru”
Saya memang diajar oleh beliau, dan mendapatkan banyak faedah ilmu saat kuliah S1 dulu. Padahal hanya satu mata kuliah saja yang saya ambil dengan beliau. Beliau sebuah sosok dosen senior yang “aura ilmu”-nya sudah terasa bahkan sejak sebelum pertama kalinya diajar. Tapi, sekadar sebagai “salah satu dosen”, apa yang membuat beliau berbeda?
Dulu zaman saya kuliah S1, khususnya saat beliau menjabat wakil dekan, beliau terkenal galak dan sangat tegas sehingga mahasiswa banyak yang segan. Menariknya saya tidak ditampakkan sisi itu. Justru saya mendapati sosok beliau yang sangat “ke-bapak-an”, apalagi kemudian ketika saya dibimbing skripsi oleh beliau. Malah saya juga menyaksikan sisi kocak beliau, suatu hari pernah saya sedang bengong di selasar Gedung II di kampus (sekarang sudah musnah, diganti Gedung B) beliau menepuk perut saya sambil berteriak “GENDUT!” kemudian literally lari sambil ngekek-ngekek ke arah saya. Kebetulan saat itu sedang sangat sepi, jadi rasanya tidak ada saksi lain. Tapi mungkin mahasiswa lain saat itu tidak akan percaya kalau saya menceritakan insiden tersebut.
Beliau adalah “Intelektual”
Beliau bukan sekadar professor administratif semata. Beliau adalah seorang begawan hukum Indonesia. Sebagai pakar hukum internasional, terkhusus dalam hukum pengungsi, ketokohan beliau sudah tidak dipertanyakan lagi. Hanya saja, untuk benar-benar memahami keunggulan level beliau dibandingkan para akademisi lain di bidang yang sama, barangkali adalah tempatnya para akademisi sejawatnya itu untuk dapat mengenali.
Sedangkan bagi orang kebanyakan beliau nampaknya lebih dikenal sebagai sosok intelektual yang tidak segan melayangkan kritik keras kepada siapapun yang baginya berbuat tidak adil. Baik itu pemerintah, pejabat public tertentu, atau bahkan kepada lingkungan kerjanya sendiri. Kritiknya selalu didukung oleh analisis yang tajam dan kokoh dengan tetap penuh hormat terhadap orang-orang yang dikritik ataupun yang mengkritik beliau.
Beliau adalah “mentor”
Mungkin kapasitas inilah yang saya paling lama merasakan. Saya tidak selalu setuju dengan opini-opini beliau, dan –sebagaimana beliau sering tekankan—memang bukan harus setuju juga. Tapi, dari lingkungan kampus, mungkin beliaulah sosok yang paling berperan dalam memicu perkembangan intelektual sejak dulu saat saya masih berstatus mahasiswa sarjana. Kini, saya pun sudah menjadi akademisi kolega sekantor beliau dan juga menyandang gelar doktor (yang studi maupun beasiswanya diperlancar antara lain oleh surat rekomendasi beliau).
Dulu beliau membimbing penelitian major saya yang pertama, yaitu skripsi. Meskipun perkembangan intelektual membawa saya untuk tidak lagi menyetujui apa yang saya dulu tulis dalam skripsi, tapi saya puas dengan apa yang bisa saya capai dengan bimbingan beliau.
Ketika awal saya menjadi dosen, kelas pertama saya di-tandem dengan beliau. Kami banyak berdiskusi tentang cara mengajar dan mendidik, dan beliau sangat memberi ruang dan memfasilitasi saya dalam mengeksplorasi ide-ide (gila) untuk diterapkan di kelas. Tidak lama kemudian, beliau pula menjadi mentor bagi saya sebagai peneliti. Hanya satu kali kami Kerjasama dalam satu proyek, tapi sering sekali saya minta nasehat dan mendapatkan faedah dari beliau.
Bahkan, mungkin banyak mahasiswa dan pembaca karya saya sekarang akan mengenali bahwa pendekatan saya sangat kental bernuansa Third World Approaches to International Law (TWAIL). Pertama saya mengenal aliran pemikiran tersebut adalah melalui buku berjudul “Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law” karya Prof. Anthony Anghie. Sedangkan yang memberikan buku tersebut kepada saya adalah Prof Sigit Riyanto. Pembacaan saya terhadap buku tersebut membola salju kepada khazanah literatur TWAIL yang luas, hingga akhirnya saya kini turut berkontribusi pada khazanah tersebut.
Beliau Adalah “Panutan”
Ketika sepeda motor saya mendekati Rumah Sakit Akademik UGM, saya mulai berfikir bahwa barangkali kata “panutan”-lah yang paling mewakili semuanya. Saya teringat respon benak saya ketika mendengar kabar wafatnya beliau adalah “who else can I look up to, now?”
Tentu kita tidak menyamakan level beliau dengan Nabi Muhammad ﷺ yang merupakan panutan paling mulia, itu urusan lain (hukum syara’). Tidak juga bermakna saya sekadar mengikut A sampai Z yang beliau lakukan, karena saya tidak harus juga selalu setuju dengan apa yang beliau contohkan.
Maksudnya, kehadiran sosok beliau adalah sebagai prima facie standar baik dan panutan sebagai seorang akademisi. Apa yang saya saksikan atas beliau selalu menjadi pertimbangan, dalam segala aspek amanah sebagai seorang akademisi. Proses kritis dalam menyaring, memodifikasi (dan lain sebagainya) sudah tentu harus dilakukan, dan ini pula antara pelajaran yang saya dapatkan dari beliau.
————-
Takdir Allah, saya tiba di ruang forensik Rumah Sakit Akademik UGM dalam keadaan jenasah beliau sudah sedang dimandikan. Ketika akhirnya saya bisa melihat jenasah beliau, sudah dikafani. Rupanya memang ketawa ketiwi lusa kemarin itulah terakhir saya melihat langsung wajah beliau.
Saat menjumpai keluarga beliau, tentu saya sadari bahwa kehilangan yang saya rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang kehilangan sosok ayah dan suami. Tapi, setidaknya bagi saya pribadi, pertanyaan yang akan selalu muncul adalah: “who else can I look up to, now?” Maka kini yang saya miliki sebagai panutan hanya kenangan-kenangan atas beliau, tidak akan ada update lagi.
Tapi memang sunatullahnya begitu: kita tidak tahu siapa yang akan “berangkat” duluan. Setidaknya kepada yang mendahului kita, terutama Begawan panutan saya Prof Sigit Riyanto, yang dapat kita lakukan ada tiga. Pertama, kita mendoakan agar dosa-dosa beliau diampuni dan amal shalih beliau diterima oleh Allah. Kedua, kita hidupkan suri tauladan yang baik dari beliau agar manfaatnya lebih luas bagi kita dan orang-orang lain dan juga kepada beliau sebagai amal jariah.
(ditulis 21 Agustus 2024)
CONDEMNATION, CONDEMNATION

I condemn all the zionist nations
For what they have done for decades
I condemn the inability of the nations
For what they fail to do for decades
Condemnation, condemnation
I condemn nations who speak of peace
For with their support many Palestinians are gone
I condemn people who speak of peace
For speaking much and doing none
Condemnation, condemnation
I condemn those who profit from your martyrdom
For the bombs bought through their businesses
I condemn those not boycotting enemies of your freedom
For your lives are cheaper than their small conveniences
Condemnation, condemnation
I condemn those who speak but cannot fight for you
For they are useless: and ‘they’ are we
I condemn those who speak but cannot fight with you
For he is useless: and ‘he’ is me
(Fajri M. Muhammadin, 2024)
NGL Thread 19062024
Ada cafe Coklat namanya. Udah berdiri sejak jaman gw masih kuliah S1 di Fak MIPA UGM dulu, dan lumayan sering ke sana selama bertahun-tahun-tahun. Banyak kenangan di sana <3
Barangkali 11 tahun lalu adalah terakhir rutin ke sana. Dalam 11 tahun belakangan ini, cuma sesekali doang ke sana. Selama 2022 akhir – 2023 akhir, ada yang paling sering dikunjungi yaitu Cafe Bestie. Gak terlalu mahal, anak saya suka banget main di situ, dan ada di rute ke sekolahnya dia. Jadi sering main ke situ. Cuma kami sekarang baru pindah rumah, jadi gak ke Bestie lagi.
Tiga dosen yang paling saya suka (tidak urut) adalah:
- Prof. Mohd. Hisham Mohd. Kamal, IIUM (pembimbing S3 saya)
- Prof. Alan Boyle, University of Edinburgh (dosen dan kaprodi waktu S2)
- Prof. Sigit Riyanto, UGM (dosen, DPS, dan “mentor” saya sampe sekarang)
- Hukum Adat
- Hukum Adat
- Hukum Adat
- Hukum Adat
- Hukum Adat
Ada yang bilang “bagus kerja dulu karena blablablabla” ada juga yang bilang “bagus langsung S2 dulu karena blablablabla”, ada yang bilang “bagus jurusan S2 linear sama S1 karena blablabla” dan lain lain, saya gak setuju sama itu semua. Kenapa gak setuju? Karena kedua pertanyaan ini bagi saya gak ada jawaban sakleknya.
Kesemua opsi di atas (kerja dulu, S2 dulu, S2 linear, S2 tidak linear, dlsb) bisa bagus ataupun tidak adalah tergantung tujuan kita. Misalnya, kalo ditanya “kuliah arsitektur bagus gak?” ya tergantung kamu mau apa. Kalo cita-cita mau jadi dokter, maka kuliah jurusan arsitektur adalah pilihan yang sangat buruk kan?
Intinya sih kita harus sesuaikan pilihan kita dengan life-plan kita, karena tujuan kita ke depanlah yang menentukan pilihan kita hari ini. Dari opsi-opsi yang ada, kita pilih mana yang mendekatkan diri kita pada tujuan ke depan.
Kalo tujuannya lebih ke pengen mendekatkan hati, coba: Ust. Syafiq Riza Basalamah, Ust. Nurul Dzikri, Ust. Hanan Attaki (Bahasa Indonesia), atau kalo suka English coba: Mufti Menk, Omar Suleiman, atau kalo ngerti bahasa Arab coba: Syekh Mansur Al-Salimi.
Semoga bisa kembali mendekat pada Allah, dan coba dibaca hadits dalam tautan ini.
Tapi kalo tujuannya mau belajar ilmu agama lebih mendalam, nanti tanya saya lagi krn nama-nama di atas gak semuanya direkomendasikan untuk tujuan itu. Sebagian da’i punya spesialisasinya masing-masing.
- Riset dulu tentang adat istiadat dan tabu-tabu di lokasi tempat KKN. Misalnya, anak Jakarta yang mau KKN di pelosok DIY/Jawa Tengah harus belajar beberapa kata kunci (njih, nuwun sewu, monggo, mari) dan kapan menggunakannya, kalo gabisa bahasa Jawa setidaknya berusaha kurangi slang khas Jakarta dan selipkan “njih” dan “matur nuwun” dll di sana-sini.
- Berusaha untuk tidak usah terlibat dalam (apalagi bikin) drama di unit kalian. Just do your job.
- Selesaikan kelengkapan administrasi SEBELUM selesai KKN. Dulu di unit saya, kami sudah planning program selesai H-4 penarikan, jadi 3 hari full untuk ngisi berkas dan borang-borang.
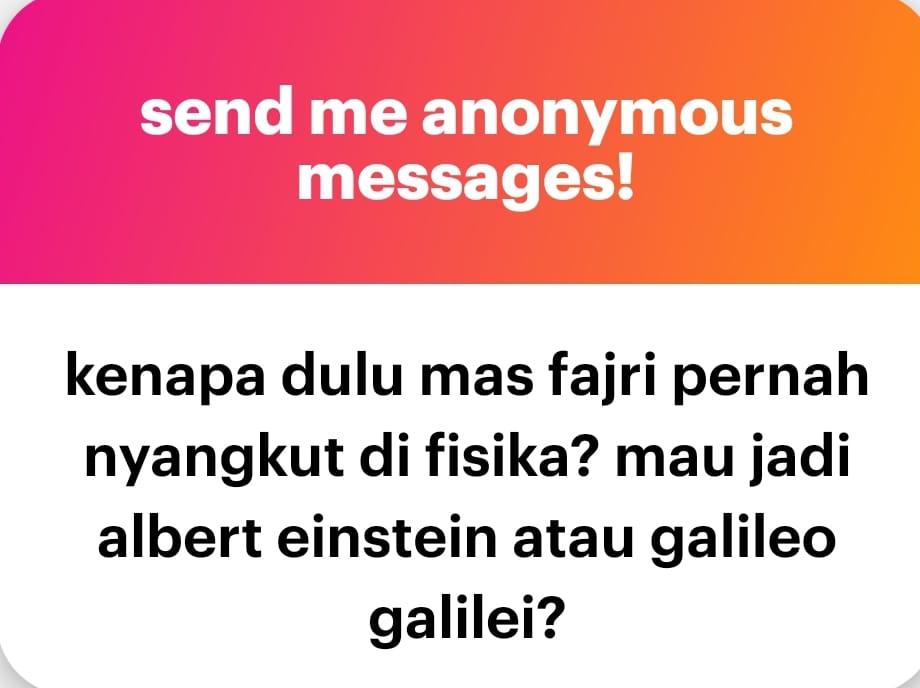
LOL karena saya anak IPA dan UTUL dulu saya milih IPC, gatau boleh pilih IPS sekalian. Pilihan pertama hukum (malah ga dapet di percobaan pertama), pilihan kedua Fisika krn saya emang suka banget fisika dan matematika. Ketika di sana, 75% udah mikir mau pindah jurusan ke hukum sesuai cita-cita awal. 25% pengen jadi Albert Einstein (mendalami Fisika Teori, beda dengan Galileo yang arahnya eksperimental ya).
Gak ada cara yang lebih baik daripada latihan-feedback-latihan-feedback sih. Kalo speaking ya ngobrol (ngomong + denger), kalo writing ya baca dan nulis (harus sepaket tuh). Feedback itu penting, maksudnya harus ada orang yang kompeten untuk bantu evaluasi.
Pertama, jadilah orang yang tepat: pantaskan dirimu sendiri, selalu berusaha jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Supaya kamu deserve better juga, jangan sampe ada orang yang high quality tapi kamunya yang gak pantes dapetin dia
Kedua, cari pilihan di saat yang tepat: Kalo menurut saya, gausah pake pacaran. Lamar langsung, taaruf yang terkontrol, lalu gas nikah aja. Kalo merasa belum siap nikah, gausah mikirin itu mending fokus mengembangkan diri. Tapi, FYI, sebenarnya gak seburuk itu lho nikah dulu lalu berjuang menggapai kesiapan sama-sama. Susah jadi pasangan yang kuat kalo belum merasakan perjuangan bersama-sama.
Ketiga, pilihlah yang tepat: keshalehan agamanya, kebaikan akhlaqnya, kecocokan (karakter dan visi misi), dan ketertarikan fisik. Bonus yang penting dipertimbangkan dampaknya: status sosial kedua keluarga (melacak potensi drama). Begitu urutannya kalo menurut saya.
Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Afrika Selatan melawan israel: Poin-Poin Penting
Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Afrika Selatan melawan israel: Poin-Poin Penting
Oleh: Fajri Matahati Muhammadin
Pada tanggal 26 Januari 2024, the International Court of Justice atau Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan Provisional Measures dalam kasus Afrika Selatan melawan israel. Pada amar putusannya ada enam butir, singkatnya adalah sebagai berikut:
(more…)Ahlan wa Sahlan Author Internasional, Bye-Bye Etika Publikasi!!
Sebagai Editor in Chief sebuah jurnal yang sedang berjuang untuk Scopus, saya sangat faham jerih payah pengelola jurnal untuk memenuhi checklist hal-hal untuk memenuhi indeksasi Scopus dan meningkatkan peringkatnya. Selamat untuk jurnal-jurnal di Indonesia yang berhasil terindeks Scopus terutama yang baru saja mendapatkannya di penghujung 2023. Bertambah lagi beban bagi saya untuk men-Scopus-kan jurnal yang saya kelola.
Pertanyaannya adalah, seberapa banyakkah kita mau menjual harga diri dan kehormatan demi mencapai indeksasi Scopus ini? Cara licik, culas, dan rendah apa yang mau kita lakukan untuk mencapai itu?
Baru saja mahasiswa ada yang mengadu kepada saya. Artikel jurnalnya telah diterima di sebuah jurnal Indonesia yang telah terindeks Scopus, alhamdulillah, dan akan terbit di tahun 2024 ini. Tapi, tetiba datang sebuah email dari pengelola jurnal tersebut kepada mahasiswa saya tersebut dan penulis-penulis lain yang naskahnya akan dimuat tahun 2024 ini, yang meminta hal yang aneh.
Karena “kebijakan” (begitu bahasanya) pengelola jurnal, semua naskah wajib memiliki afiliasi internasional. Memang, Scopus menginginkan jurnal yang memiliki keanekaragaman latar belakang penulis. Akan tetapi, yang diminta sekadar menambahkan saja seorang co-author berafiliasi non-Indonesia. Tidak disyaratkan penambahan penulis tersebut diiringi dengan penambahan substansi apapun.
Menariknya, meskipun dalam email pengelola jurnal disebut sebagai “kebijakan” pengelola, tapi “kebijakan” tersebut tidak nampak tertulis di website jurnal sama sekali. Maka, “kebijakan” ini tidak dapat diketahui oleh calon penulis yang masih berkesempatan mencari penulis internasional untuk sama-sama berkontribusi dalam penulisan. Yang mengetahui hanya penerima email saja, yaitu penulis yang naskah-naskahnya sudah selesai tanpa adanya penulis internasional.
Maka bagi saya jelas: secara tegas jurnal ini memerintahkan adanya orang yang “menumpang nama”.
Hal ini adalah sebuah pelanggaran etika publikasi yang dikenal dengan guest authorship atau gift authorship, yang telah lama diulas oleh pedoman-pedoman etika publikasi di lembaga publikasi ternama semisal Elsavier atau yang lainya. Mungkin ini juga alasan kenapa para pengelola jurnal ini tidak mencantumkan “kebijakan” wajibnya co-author internasional, karena nampak jelas membuka pintu pada guest/gift authorship. Padahal, jurnal-jurnal ini di websitenya mencantumkan komitmennya untuk mematuhi etika publikasi (pret).
Sebenarnya pelanggaran etika ini banyak terjadi dan kita tahu sama tahu. Banyak sekali dosen yang malas berfikir dan berinovasi tapi rakus sekali urusan kenaikan pangkat dan insentif akhirnya meminta (terkadang memerintah) koleganya untuk memasukkan dirinya sebagai penulis padahal kontribusinya nol. Tapi sebagai pengelola jurnal, dalam mayoritas kasus kita tidak bisa membedakan mana yang numpang nama dan yang betul-betul berperan dalam penulisan. Maka, dari perspektif pengelola jurnal, ya sudahlah.
Tapi, ketika malah pengelola jurnal yang memerintahkan dilakukannya pelanggaran etika tersebut, ini sudah sangat keterlaluan sekali. Apalagi jurnal ini adalah jurnal hukum yang dikelola oleh akademisi ilmu hukum juga yang seharusnya menjadi poros terdepan dalam membenahi hukum di negara ini. Atau, jangan-jangan perilaku tidak etik dan korup memang merupakan budaya hukum Indonesia yang riil tapi kita tidak mau mengakuinya saja?
Pertanyaan menariknya: bukankah menarik, kalau saya mengirimkan screenshot email “kebijakan” jurnal tersebut kepada Scopus untuk menunjukkan perilaku tidak etisnya ini? 😈😈😈😈😈😈😈
Link ke daftar praktek-praktek jurnal yang tidak etis yang pernah saya jumpai atau dengar dari korban langsung.