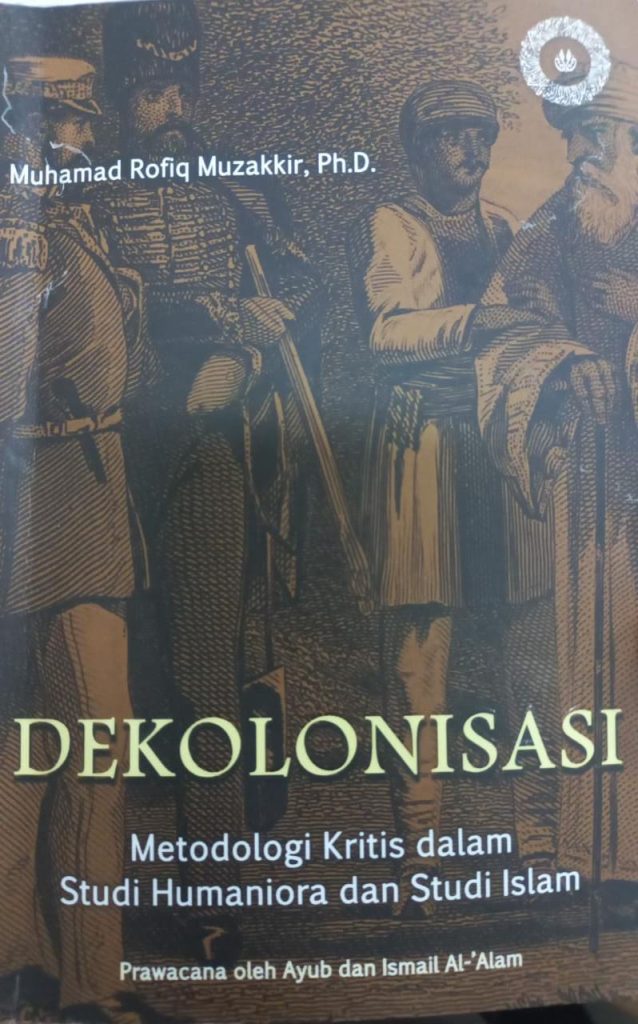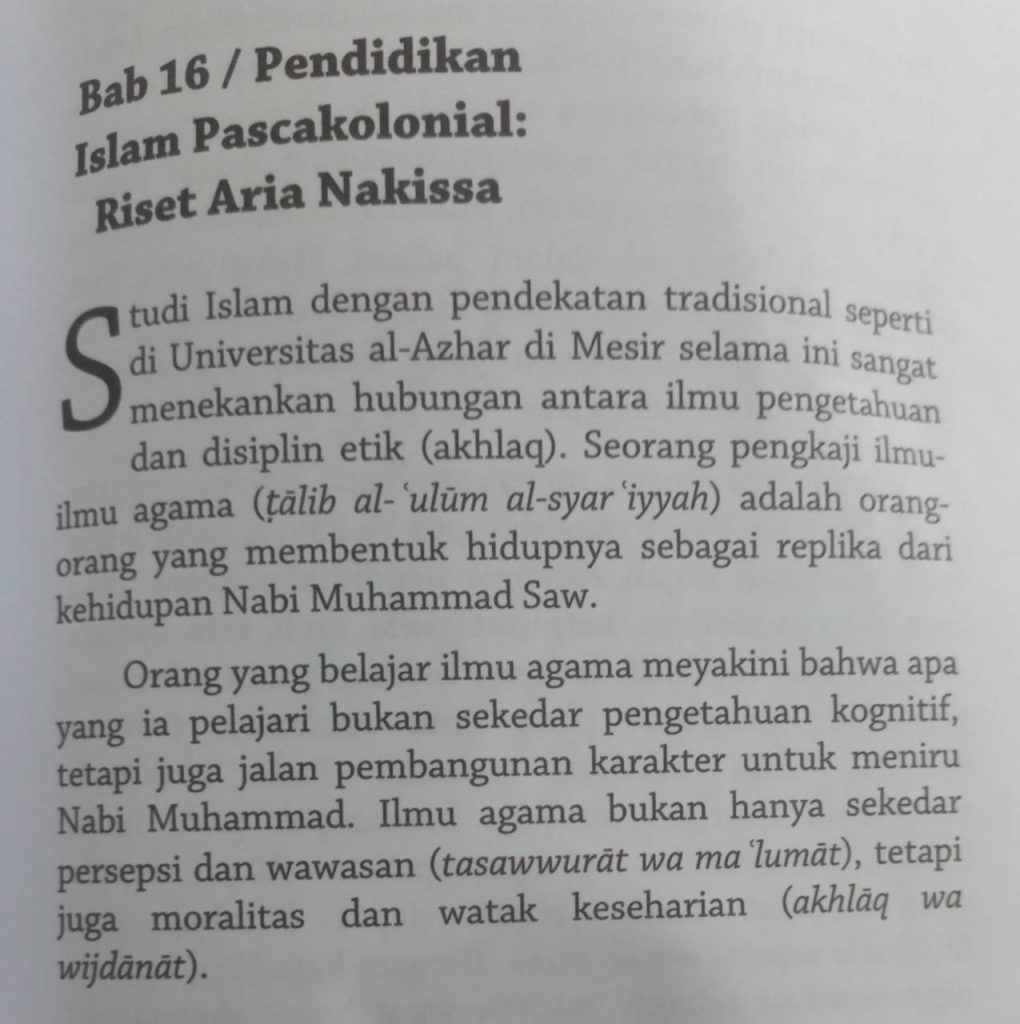Home » 2023
Yearly Archives: 2023
Refleksi (Curcol?) Buku: Dampak Ilmu pada Kesalehan Personal
Buku “Dekolonisasi: Metodologi Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam” yang diterbitkan oleh Yayasan Bentala adalah kompilasi catatan-catatan oleh penulisnya, Dr. Muhamad Rofiq Muzakkir, selama studi doktoralnya di Arizon State University.
Buku ini sangat saya rekomendasikan, terutama bagi sesiapa yang mempelajari ilmu-ilmu sosio-humaniora. Bahkan untuk bidang hukum, meskipun tidak secara khusus mengkaji hukum Islam, akan sangat penting membaca buku ini karena akan sulit untuk orang Indonesia belajar hukum dan tidak bersinggungan dengan masyarakat yang beragama (apapun, meskipun mayoritasnya Islam) dan masyarakat dengan nuansa adat yang kental (yang bersifat religio magis). Apalagi, di bangku perkuliahan hukum biasanya sangat sekuler konsep-konsepnya, meskipun sesekali ada bau-bau agamanya sedikit.
Yang ingin saya ulas sedikit (barangkali agak curcol) adalah refleksi saya terhadap Bab 16: Pendidikan Islam Pascakolonial: Riset Aria Nakissa. Bab-bab di buku ini sangat pendek dan masing-masingnya bisa membawa perenungan yang panjang sekali. Tapi ada satu renungan spesifik yang ingin saya sampaikan.
Aria Nakissa mengkaji dampak pendidikan ala Barat terhadap pendidikan Islam, khususnya di Mesir. Salah satu dampak yang disoroti adalah mulai berkurangnya dampak ilmu agama kepada karakter pribadi. Tentu seharusnya seseorang yang makin mempelajari ilmu agama akan semakin mempraktekkan apa yang ia ketahui. Sehingga, harusnya mereka adalah orang-orang yang paling baik.
Kalau dipikir-pikir, hal ini dari dulu memang merupakan sebuah ekspektasi saya pribadi (dan, nampaknya, banyak orang juga) terhadap pakar dan pembelajar ilmu agama secara khusus ataupun sosok terpelajar dan/atau pendidik secara umum. Sebagaimana kata pepatah, bagaikan padi yang semakin berisi semakin merunduk.
Karena itulah, meskipun saya bukan pakar agama, tapi sebagai pendidik di bidang hukum saya setengah mati berusaha (misalnya) se-tertib mungkin di jalan raya, tidak buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Saya masih jauh dari sempurna, tapi saya benar-benar berusaha. Apalagi, ketika menuntaskan Ph.D Thesis, ada satu bab khusus yang membahas amanah dan khiyanat dalam konteks hukum, saya semakin waspada kalau berjanji. Lebih berusaha untuk tidak asal ngomong “insyaAllah” atau “ya” sekadar karena tidak enak, kalau saya tidak yakin bisa memenuhi.
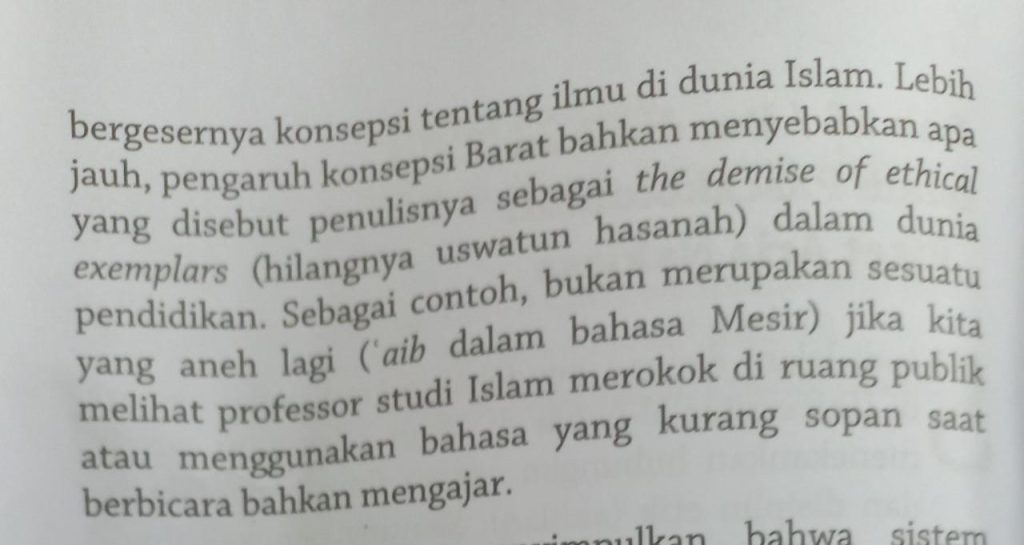
Katanya, akibat pendidikan Barat, mulai nampak ahli-ahli ilmu agama yang kelakuannya tidak mencerminkan hal tersebut. Aria Nakissa menyebut contoh Professor studi Islam yang merokok di ruang publik atau menggunakan bahasa yang kurang sopan ketika mengajar.
Di sini, saya bukan pakar agama tapi saya berusaha belajar. Saya berusaha ke sana-sini kepo sana kepo sini kepada para asatiz dan masyaikh (baik langsung maupun melalui rekaman ceramah ataupun karya tulis) untuk belajar. Dalam banyak hal, alhamdulillah saya mendapatkan bukan hanya ilmu secara substansi tapi belajar banyak dari kesalehan personal dari banyak asatiz dan masyaikh ini.
Sekali-sekali mendengar kabar asatiz dan masyaikh yang ‘miring’, saya selalu berusaha ber-husnudzon dengan menganggap itu minority report saja dan/atau saya belum tahu kebenaran yang utuh terkait kabar-kabar tersebut.
Hanya saja, yang sedikit kecewa adalah ketika ‘statistik’ pengalaman personal yang berbicara. Saya kebetulan memiliki pengalaman bekerjasama dengan berbagai kalangan. Ada pengalaman kerjasama yang manis, ada yang harus berpahit-pahit tapi alhamdulillah berakhir tuntas, tapi ada juga kerjasama yang akhirnya kemudian gagal menuntaskan tujuan.
Tentu saya juga pastinya punya andil dalam kegagalan-kegagalan ini. Tapi, selain itu, banyak kasus gagal yang berakhir demikian karena rekan kerjasama ini tiba-tiba menyublim karena satu dan lain hal. Kadang kita ketahui alasannya, kadang juga tidak diketahui karena ya menyublim saja begitu.
Yang agak mengecewakan adalah karena kok mayoritas kerjasama gagal karena rekan yang menyublim ini, adalah mayoritasnya dari kalangan asatiz dan thulabul ‘ilmi.
Kedudukan Hadits Ahkam yang Sanadnya Dha’if: Imam Ahmad
Berikut faedah bagus yang saya dapatkan di salah satu grup WhatsApp ketika para masyaikh berdiskusi tentang kedudukan hadits ahkam yang sanadnya dha’if. Semoga bermanfaat:
(more…)Cara Mensitasi Antologi/Chapter Book: Banyak Mahasiswa Sering Salah!!!
Selama pengalaman saya mengoreksi banyak skripsi, thesis, paper, bahkan artikel jurnal, saya menemukan bahwa masih banyak mahasiswa dan penulis yang keliru dalam mensitasi Antologi atau Chapter Book. Ini bisa bermasalah secara etika penulisan! Yuk kita bahas!
Read MorePBB Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Mas Dosen Hukum Internasional
Ketika seorang tokoh agama menyatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa menjadi sumber hukum Islam, langsung muncul perdebatan di mana-mana. Sebagian berkata “Sumber hukum Islam itu cuma Quran Sunnah Ijma Qiyas!”, sebagian lain berkata “PBB itu Taghut!”. Tapi, bagaimana kebenarannya? Nah, mari kita coba dalami.
.
Sumber Hukum Cuma Qur’an Sunnah Ijma Qiyas?
Kalau sekilas melihat literatur ushul fiqih klasik, nampaknya tidak ada tentang sumber hukum sama sekali. Pasalnya, karya-karya tersebut berbahasa Arab dan bukan berbahasa Indonesia. Akan tetapi, kalau merujuk ke karya-karya berbahasa Indonesia banyak yang menyebutkan sumber hukum Islam (atau “source of Islamic law” untuk karya berbahasa Inggris) mencakup hal-hal selain itu, misalnya: ‘urf, istihsan, maslahat mursalah, dan lain sebagainya.
Di sini saya penting menyebut “perintah penguasa” (qanun) dan “kontrak” (akad). Kita ketahui bahwa keduanya wajib kita patuhi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat (ada dalilnya syarih), tapi mayoritas literatur yang saya baca tidak menyebutkan keduanya sebagai “sumber hukum” kecuali satu saja sependek yang saya tahu (yaitu karya alm. M. Cherif Bassiouni).
Sedangkan, kalau kami yang kuliah hukum konvensional, maka peraturan perundang-undangan dan perjanjian itu ya disebut dengan “sumber hukum”. Alasannya sederhana, yaitu karena isinya aturan yang harus ditaati. Dari kacamata kami ini, dan ditunjang literatur hukum Islam berbahasa Indonesia, ya kesemuanya ini ya tidak mustahil disebut sebagai sumber hukum. Bedanya, dibagi ke sumber hukum primer (Quran, Sunnah, Ijma) dan sumber hukum sekunder yang merupakan ‘pengolahan lanjutan’ oleh manusia.
Di sini, mungkin ada pertanyaan jadinya: apakah perintah penguasa dan kontrak bisa dimasukkan sebagai “sumber hukum sekunder”? Atau, jangan-jangan istilah “sumber hukum” yang dimaksud pada kedua konteks ini sebenarnya mengacu pada konsep yang berbeda total?
.
Piagam PBB itu Makhluq Apa Sih?
Sebelum kita tahu status hukum Piagam PBB, tentu kita harus tahu dia makhluq apa. Sebahagian pendapat mengatakan bahwa “dia adalah hukum buatan orang kafir”. Pada dasarnya, memang betul yang pertama merumuskan Piagam PBB itu kebanyakannya adalah non-Muslim.
Tapi, sebenarnya, pada dasarnya Piagam PBB itu merupakan perjanjian antar negara. Kebanyakan negara yang menyepakati Piagam PBB pada San Fransisco Conference 1945 memang mayoritas non-Muslim, tapi ada juga beberapa negara mayoritas Muslim, misalnya Saudi Arabia dan Lebanon dan Mesir dan Suriah. Wakil-wakil negara duduk bersama dan menyepakati butir-butir tertentu di antara mereka.
Bagaimana hukumnya negara Islam berperjanjian dengan negara mayoritas non-Muslim? Jawabnya: sebagaimana disampaikan Syaikh Salih Al-Fawzan, boleh sepanjang ada maslahatnya. Tentunya juga kalau objek perjanjian tidak bertentangan dengan Syariah.
Selesaikah bahasannya? Belum. Saya sebut bahwa “pada dasarnya” Piagam PBB itu merupakan perjanjian antar negara karena dalam praktek hukum internasional ada beberapa model perjanjian yang bisa jadi akan memiliki dampak hukum yang berbeda.
Piagam PBB bukan perjanjian internasional kontraktual biasa (sebagaimana misalnya negara A dan B membuat perjanjian expor-impor lato lato), melainkan sebuah Constitutive Instrument yaitu pendirian sebuah organisasi internasional. Maksudnya, isi perjanjian tersebut adalah mendirikan sebuah organisasi baru yaitu PBB.
Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila sekelompok orang bersepakat membentuk organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu? Sampai di sini, nampaknya tidak ada masalah ya. Meskipun ada sedikit diskursus kontemporer tentang apakah dalam hukum Islam dapat dibentuk sebuah Lembaga yang memiliki personalitas hukum terpisah dari orang-orang yang mendirikannya.
Apakah dapat meng-qiyas-kan hukum orang membuat organisasi dengan negara membuat organisasi? Nah, ini perlu kajian lebih lanjut. Akan tetapi, ada satu poin yang mungkin bisa dijadikan acuan awal:
Otoritas apakah yang diberikan oleh para negara anggota kepada organisasinya? Ada organisasi internasional yang berfungsi sekadar sebagai forum saja dengan negara anggota tetap berada di puncak komando, semisal Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Ada pula organisasi internasional yang bersifat supranasional, maksudnya ia menjadi badan pemerintah berdaulat di atas anggota-anggotanya (hanya satu contoh: Uni Eropa). PBB bagaimana statusnya?
Satu jenis perjanjian internasional yang ingin saya perkenalkan (bisa saja beririsan dengan jenis sebelumnya) adalah law-making treaty. Panjang penjelasan tentang law-making treaty ini, bisa baca di buku kami (download di sini). Tapi sederhananya, Catherine Brölmann menyebut bahwa perjanjian law-making ini disepakati untuk ‘above’ (di atas) negara-negara yang bersepakat dan dicita-citakan berlaku seuniversal mungkin, selayaknya undang-undang bagi sebuah warga negara. Kontraskan dengan perjanjian kontraktual biasa yang mengikat pihak-pihak yang sejajar. Konstruksi perjanjian semacam ini seakan-akan mengakui ada ‘rezim masyarakat internasional’ yang berkuasa di atas kedaulatan negara.
Bagaimana hukumnya kalau seperti ini?
.
Operasional PBB: Menimbang Maslahat dan Mudharat
Apakah PBB memberi lebih banyak maslahat dibandingkan mudharat, atau malah sebaliknya?
Untuk mengenal operasional PBB dengan lebih akurat dan bukan cuma mitos berbasiskan ‘dari sedikit yang saya tahu’, perlu mengexplorasi: Piagam PBB itu sendiri, organ-organ PBB dengan lebih rinci, juga Lembaga-lembaga lainnya di bawah PBB. Tidak cukup membaca Piagam PBB saja, melainkan juga perlu banyak dokumen dan instrument turunannya, apalagi insiden-insiden tertentu yang bisa terisolasi atau bisa juga sistematis (tapi belum dicek yang benar).
Mungkin perlu satu mata kuliah 4 SKS untuk sekadar mengenalkan PBB. Tapi mungkin sederhananya dalam satu kalimat: PBB bercita-cita mewujudkan perdamaian dunia, yang bukan cuma ‘tidak adanya perang’ tapi juga mengisinya dengan kesejahteraan. Karena itulah, PBB memiliki organ yang merespon konflik internasional semisal Dewan Keamanan, tapi juga punya badan-badan spesialis semisal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO), dan lain-lain.
Di sinilah, sulit untuk menghakimi PBB dengan “gebyah uyah”. Sebab, setiap pasal substantif Piagam PBB, organ, Lembaga, atau agensi, atau Lembaga lainnya di bawah PBB, memiliki diskursusnya masing-masing.
Lalu, Dewan Keamanan PBB sering kita hujat karena macet ketika berurusan soal Palestina, tentunya akibat hak veto yang dimiliki Amerika Serikat. Suriah pun, dalam perang tahun 2011 (sampai sekarang), Dewan Keamanan juga tidak bisa berbuat apa-apa akibat hak veto dari Rusia dan Cina. Dan, apakah kita ikhlas kalau organ sekuat dan seberbahaya Dewan Keamanan hanya dipegang oleh 15 negara, dibandingkan keseluruhan PBB yang anggotanya 193 negara Akan tetapi, fungsi keamanan PBB yang digawangi oleh Dewan Keamanan, relatif sukses dari sudut jumlah konflik antar negara. Mayoritias konflik sekarang didominasi konflik internal negara, meskipun kemudian terkadang dijadikan ‘proxy war’, tapi bagaimana statistik jumlah perang? Meskipun kita sedih sekali dengan Palestina dan Suriah, tapi jumlah perang antar negara setelah berdirinya PBB jauh berkurang dibandingkan sebelumnya.
Sedangkan Majelis Umum PBB nampak jadi forum yang sangat vokal membela Palestina karena hak veto tidak berdampak. PBB mengakui Palestina sebagai negara, meminta ‘fatwa hukum’ dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang kemudian secara tegas ber’fatwa’ bahwa pembangunan tembok Jerusalem oleh Israel adalah bertentangan dengan hukum internasional, semuanya merupakan peran Majelis Umum PBB. Sayangnya, apa follow up-nya? Apa konkritnya? Tidak ada, karena Majelis Umum PBB tidak bisa mengeluarkan resolusi yang mengikat secara hukum untuk hal-hal seperti ini. Akhirnya, jadi seperti macan ompong saja.
Organisasi Kesehatan Dunia-lah (WHO) yang menghapus homoseksualitas dari Diagnostic Statistic Manual (pedoman diagnosis gangguan kejiwaan) III pada tahun 1973. Hal tersebut adalah bagian dari normalisasi LGBT yang akhirnya makin ke sini makin sangat marak. Tapi, betapa banyak standar Kesehatan dan medis yang begitu bermanfaat yang dibuat oleh WHO. Misalnya, mereka bersama dengan FAO menyusun Codex Alimentarius yang merupakan standar sanitasi dan fito-sanitasi pangan. Bahkan Diagnostic Statistic Manual tadi, sebagian besarnya membantu memberikan standar diagnosis beraneka jenis gangguan kejiwaan (please jangan bilang “gangguan jiwa mah obatnya dzikir dan bersyukur aja”).
Ada pula yang berpendapat bahwa meskipun PBB banyak kekurangan, tapi di situlah Indonesia dan umat Islam bisa berkontribusi untuk memperbaiki. Ada benarnya, karena (misalnya) Indonesia mendapatkan peluang peran besar ketika menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, melihat konstruksi kekuasaan kelembagaan di PBB, sejauh mana negara-negara selain P5 (Amerika Serikat, Cina, Perancis, Britania Raya, dan Rusia) memiliki potensi untuk benar-benar melakukan perubahan kecuali atas restu negara-negara P5 tersebut? Realitanya, apakah “kerusakan-kerusakan” PBB tersebut membaik setelah berdiri selama 78 tahun?
PS: ketika membahas plus minus dengan dipisahkan oleh “tapi”, seringkali terasa bahwa apa yang disebut setelah “tapi” itulah yang ditekankan. Jadi sengaja saya gentian plus minusnya sebelum dan sesudah “tapi” supaya menghindari terasa tendensius, ceritanya sok misterius.
Ini baru menyebut tiga saja, dan itupun hanya sedikit sekali contohnya dan sekilas saja. Setiap organ, badan, agensi, dan Lembaga lain di bawah PBB, bisa dikaji dengan sangat komprehensif dan panjang. Bagaimana menilainya? Apakah kita bisa gebyah uyah menilai PBB secara keseluruhan batil? Atau, bagaimana caranya?
.
Kesimpulannya?
Posisi (kesimpulan) saya pribadi tentang PBB bukan tujuan saya menyusun tulisan ini. Beberapa kawan yang mengenal pemikiran saya tentang Siyar kontemporer pasti sudah bisa menebak apa kesimpulan saya, atau malah sudah pernah saya ceritakan. Sebagian opini saya tertulis di buku saya yang bisa dibeli di sini (100% penjualan untuk Yayasan Bentala).
Tujuan saya menulis ini adalah untuk mengangkat beberapa di antara pertanyaan yang mungkin penting dieksplorasi untuk menilai status Piagam PBB dalam Syariat. Bagi para penulis dan akademisi, mungkin bisa jadi inspirasi untuk melakukan kajian-kajian yang baik dan lebih komprehensif. Sebagai peneliti yang sudah mengkaji isu hukum internasional dan Islam selama beberapa tahun dan inshaAllah masih setrong, menurut saya ini dialog yang menarik dan baik yang memerlukan dialog antara pihak-pihak yang faham syariahnya dan juga faham hukum internasionalnya.
Edit: pandangan saya, diskursus Piagam PBB dalam “Fiqih Peradaban” rasanya baru bisa lebih diselami kalau sudah clear dulu makhluq apa itu PBB, bagaimana struktur dan operasionalnya, dan bagaimana syariat Islam berinteraksi dengan hal-hal “internasional” seperti ini. Semacam kerangka ‘usuliyyah’-nya lah begitu barangkali pembahasaannya, di sini mungkin para usuliyyin bisa berdialog dengan pakar-pakar hukum internasional supaya lebih jelas duduk perkaranya sebelum masuk pada produk-produk turunan.
Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Konsentrasi (Khusus S1 Fakultas Hukum UGM)
Konsentrasi adalah salah satu pilihan yang penting dilakukan mahasiswa Fak Hukum UGM di semester 5 atau 6. Tapi ada dua isu: (a) banyak kebingungan di sebagian mahasiswa tentang serba-serbi konsentrasi, dan (b) banyak kesalahpahaman tentang konsentrasi. Karena itu, berikut beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari mahasiswa tentang konsentrasi beserta jawaban dari saya.
Post ini adalah living post jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen atau japri saya, inshaAllah saya coba jawab. Boleh tanya tentang konsen mana saja, kalau tentang konsen selain Hukum Internasional akan saya coba tanyakan ke dosen di departemen yang relevan. Tapi, jangan tanya tentang prosedur ya, mayoritas jawaban ada di buku pedoman 😊
======================
LIST PERTANYAAN (SEMENTARA)
Pertanyaan Pertama: Konsentrasi Itu Apa Sih?
Pertanyaan Kedua: Apa Betul, Pilihan Konsentrasi Menentukan Karir Masa Depan?
Pertanyaan Ketiga: Lantas, Konsentrasi Tidak Ada Hubungan Dengan Karir Masa Depan?
Pertanyaan Keempat: Apa Pertimbangan Memilih Konsentrasi?
Pertanyaan Kelima: Apa Pertimbangan Memilih Mata Kuliah Konsentrasi?
Pertanyaan Keenam: Lebih Valid Minta Nasehat Kakak Tingkat atau Dosen?
Pertanyaan Ketujuh: Bagaimana Cara Memilih Pembimbing Skripsi?
Pertanyaan Kedelapan: Bisa Ganti Pembimbing Skripsi?
Pertanyaan Kesembilan: Daftar Konsentrasi Hukum Internasional Disuruh Mengisi Judul Skripsi, Apakah Mengikat?
Pertanyaan Kesepuluh: Skripsi Itu Susah Nggak Sih?
(silahkan tambahkan kalau ada pertanyaan lain)
Bonus Pesan Sponsor: Pamer Dikit Publikasi Mahasiswa Konsen Hukum Internasional
========================
JAWABAN
.
Pertanyaan Pertama: Konsentrasi Itu Apa Sih?
Sederhananya, “konsentrasi” di prodi S1 Fakultas Hukum UGM itu adalah semacam program peminatan menuju ke skripsi. Mahasiswa di semester 5 atau 6 (tergantung IUP atau Reguler) akan mengambil sekian mata kuliah khusus yang diampu oleh salah satu departemen, dan tentunya departemen kan mewakili salah satu bidang hukum ya.. Misalnya Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara dll.
Total mata kuliah adalah 7 atau 5 tergantung ambil program reguler atau IUP (14 atau 15 SKS) yang mayoritasnya harus dari departemen tempat kita ambil konsentrasi, tapi bisa juga ambil sebagian mata kuliah dari departemen lain lho untuk variasi dan mix-match ilmu.
Di penghujung, kita akan menulis skripsi yang diampu pembimbing dari departemen tersebut (sebagian departemen, bisa mulai menulis ketika masih mengambil mata kuliah konsentrasi) lalu kalau selesai akan disidang.
.
Pertanyaan Kedua: Apa Betul, Pilihan Konsentrasi Menentukan Karir Masa Depan?
Jawaban ringkasnya: kalau ‘menentukan’, TIDAK.
Ternyata, banyak yang keliru mengira bahwa untuk menjadi corporate lawyer harus ambil konsentrasi hukum bisnis, sehingga kalau mengambil konsentrasi lain tidak bisa menjadi corporate lawyer. Kenapa keliru? Setidaknya ada tiga alasan:
Pertama, dari sekian banyak lowongan kerja khas hukum yang pernah saya lihat, nyaris tidak ada yang mencantumkan syarat konsentrasi. Hanya satu saja dulu (lupa di mana) yang secara khusus meminta pelamar berkonsentrasi bisnis atau perdata, sedangkan sekian ratus lowongan hukum lainnya tidak menyebutkan apapun.
Kedua, program S1 itu mensyaratkan 145 SKS untuk mendapatkan gelar sarjana. Sedangkan konsentrasi itu hanya 18 atau 19 SKS (14 atau 15 SKS kelas, 4 SKS skripsi), atau tidak sampai seperlimanya lho. Tidak mungkin standar kompetensi seorang sarjana hukum hanya ditentukan oleh konsentrasi pilihannya semata.
Ketiga, secara empirik ternyata banyak sekali yang kerja tidak sesuai konsentrasinya. Ada yang konsentrasi Hukum Administrasi Negara, kerja di ASEAN (organisasi internasional). Ada yang konsentrasi hukum bisnis, sekarang jadi diplomat di Kemenlu. Ada yang konsentrasi pidana, jadi dosen hukum perdata. Ada yang konsentrasi hukum internasional, sekarang jadi corporate lawyer. Ada yang konsentrasi perdata, sekarang jadi jaksa. Dan lain sebagainya.
***
FYI, menurut pengalaman sebagian alumni yang kerja jadi corporate lawyer (sebagian lain gak gw tanya soalnya), apa yang dipelajari di kampus –bahkan yang konsen hukum bisnis—itu nyaris tidak berpengaruh waktu jadi lawyer. Seakan-akan belajar dari awal lagi, sampe yang dulunya konsen hukum bisnis itu tidak punya ‘starting point lebih’ yang signifikan dibandingkan yang konsennya bukan hukum bisnis lho.
.
Pertanyaan Ketiga: Lantas, Konsentrasi Tidak Ada Hubungan Dengan Karir Masa Depan?
Kalau ‘menentukan’, tidak. Kalau ‘berkontribusi’, MUNGKIN.
Semua pilihan kita seyogianya dibuat dengan memikirkan tujuan kita ke depan. Kalau belum tahu apa tujuan kita, maka tujuannya sementara adalah mencari apa tujuan kita itu. Tidak ada orang yang bilang “Saya mau jadi dokter! Masuk fakultas teknik aaaaaaaaaaaaah”.
Maka jika ada pilihan jurusan kuliah (waktu kita SMA), baiknya memilih sesuai cita-cita mau jadi apa. Kalau sudah sedang kuliah lalu dapat pilihan mata kuliah, baiknya mengambil pilihan yang memberikan pengetahuan atau keterampilan yang kiranya lebih kita butuhkan untuk cita-cita ke depan tersebut. Konsentrasi pun demikian.
Lho, katanya belum tentu?
Nah, masa depan kita kan nggak tau. Itu Allah yang menentukan. Sambil jalan nanti kita bisa punya minat dan kesempatan baru, jangankan kerja di bidang yang konsentrasinya lain, bisa juga malah kerja di bidang yang bahkan non-hukum. Tapi, kita kan tidak bisa meramal ya. Membuat rencana, mengambil pilihan-pilihan untuk membangun rencana tersebut, itu adalah bagian dari ikhtiar (usaha baik) kita. Wajar kalau kita bercita-cita bekerja di bidang hukum tata negara, lalu kita memilih untuk mengambil kuliah-kuliah yang khusus tentang hukum tata negara ketika ada pilihan untuk itu.
Makanya, pemilihan konsentrasi ini bukannya tidak penting. Justru, dia salah satu cara untuk mengupayakan cita-cita kita. Hanya saja, dia bukan satu-satunya cara dan bahkan bukan cara yang paling dominan untuk mencapai cita-cita kita itu.
.
Pertanyaan Keempat: Apa Pertimbangan Memilih Konsentrasi?
Secara umum, sebagaimana jawaban pertanyaan sebelumnya, ya pilih sesuai cita-cita ke depan. Masalahnya, kan nggak selalu semudah itu ya. Mungkin masih labil sama pilihan, atau kadang minat nggak sesuai sama nilai, dan lain sebagainya. Jadiiii ini ada beberapa pointers saja:
- Paling utama, eliminasi dulu konsen yang (a) nilai kamu gak cukup dan kamu ga se-pengen itu untuk nunggu ngulang dulu, dan (b) yang tidak terbuka untuk program kamu, khususnya untuk IUP yang pilihan konsen-nya cuma empat.
- Pilih yang kiranya lebih sesuai dengan cita-cita (klo udah punya yang clear)
- Pilih yang mata kuliah prasyaratnya dulu kamu enjoy.
- Pilih yang mayoritas mata kuliahnya lebih kelihatan menarik.
- Pilih yang dosen-dosennya lebih keliatan menyenangkan dan/atau keren kalo nulis surat rekomendasi.
Makin banyak poin yang bisa dipenuhi, makin bagus. Tapi kalo nggak semuanya, ya nggak papa juga. Yang penting, mungkin itu aja yang dipertimbangkan. FYI, sangat mungkin seseorang sebenernya pengen jadi corporate lawyer tapi suka banget sama dosen dan kuliah di konsen HTN jadi dia tetep konsen HTN aja supaya happy dan enak lulusnya kemudian lulus tetep daftar corporate law firm (lihat juga catatan terakhir di Pertanyaan Kedua).
.
Pertanyaan Kelima: Apa Pertimbangan Memilih Mata Kuliah Konsentrasi?
Konteks pertanyaan ini: di mayoritas konsentrasi, ada mata kuliah wajib dan ada juga mata kuliah pilihan, tapi harus mengambil total jumlah mata kuliah konsentrasi sekian (7 untuk reguler, 5 untuk IUP). Kalau yang wajib ya artinya harus diambil ya. Maka pertanyaan ini fokus ke mata kuliah pilihan.
Mata kuliah pilihan ini bisa kita pilih dari departemen kita sendiri, ataupun dari departemen lainnya. Saya sendiri dulu mengambil dua mata kuliah lintas konsentrasi, satu dari Hukum Islam satu lagi dari Hukum Administrasi Negara. Bagaimana memilihnya?
Ada beberapa pointers:
- Mana yang kontennya kita butuhkan untuk cita-cita kita, yang bisa jadi membutuhkan pengetahuan hukum yang multidisipliner.
- Mana yang kelihatannya menarik dan kita bisa enjoy, baik dari segi konten maupun dosen pengajarnya.
- Mana yang lebih mudah/susah nilainya, mempertimbangkan trend tahun sebelumnya dan jenis peniliannya.
- Jangan takut mix and match dengan mata kuliah dari department lain, kalo kamu emang merasa pengen dan butuh!
.
Pertanyaan Keenam: Lebih Valid Minta Nasehat Kakak Tingkat atau Dosen?
Di satu sisi, pengalaman mahasiswa diajar atau dibimbing oleh dosen tertentu atau mengambil mata kuliah tertentu, tentu akan valid sebagai pengalaman empiris. Sangat penting bertanya kepada kakak tingkat yang sudah pernah mengambil mata kuliah atau diajar/dibimbing dosen tertentu untuk tahu seperti apa prospek dan tantangannya juga bagaimana mengatasinya.
Di sisi lain, sebagai dosen yang pernah diajar oleh dosen-dosen yang kini jadi kolega, saya melihat banyak sekali miskonsepsi oleh mahasiswa. Seringkali mahasiswa mengalami sesuatu dengan kelas atau dosen tertentu, tapi mereka salah memahami apa yang mereka alami sehingga menyimpulkan dengan keliru.
Balik ke sisi yang pertama tadi, mahasiswa juga sering kok menyimpulkan dengan benar. Atau, kadang juga informasinya benar tapi parsial. Nah, terus gimana dong?
Jawabannya cliché: harus minta nasehat keduanya. Idealnya kita membina hubungan baik dengan DPA kita. Mereka belum tentu merupakan dosen di departemen tempat kita konsentrasi. Selain itu, ada baiknya juga kita bangun relasi dengan setidaknya sebagian dosen, atau kalaupun tidak jangan ragu untuk coba mulai dekati dosen untuk minta nasehat. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah dibilang “maaf saya sedang sibuk”, dan kita tinggal mencari dosen lain untuk ditanya.
Selain itu, tanya-tanya juga ke kakak kelas. Kombinasikan informasi yang didapatkan, mudah-mudahan bisa dapet konklusi yang lebih akurat.
.
Pertanyaan Ketujuh: Bagaimana Cara Memilih Pembimbing Skripsi?
Terkait memilih pembimbing skripsi, setiap departemen bisa punya praktek yang berbeda-beda. Ada departemen yang mahasiswanya harus mengajukan judul, kemudian ketua departemen yang memilihkan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) sesuai tema yang diajukan. Kalau sistemnya seperti ini, maka kemungkinan besar mendapatkan pembimbing yang bidang risetnya sesuai dengan judul yang kita ajukan. Ini juga bisa jadi strategi, kalau mau dapat dosen tertentu maka pilihlah tema yang paling sesuai dengan bidang si dosen tersebut. Bahkan, kadang-kadang bisa approach personal ke ketua departemen dan dosen yang bersangkutan, siapa tahu dikasih. Tapi, perlu diketahui bahwa ini bukan pertimbangan utama. Pemerataan jumlah bimbingan juga dipertimbangkan, karena kasihan kalau ada dosen yang bimbingannya terlalu banyak dan dosen lain yang malah tidak ada bimbingan.
Tapi, tidak semua departemen seperti itu. Departemen Hukum Internasional, misalnya, dari awal kalian daftar konsentrasi itu langsung dikasih DPS. Harapannya adalah supaya (kalau mau ya) bisa penjajakan dari awal, eksplorasi, siapa tahu bisa ikutan proyek dosen tersebut. Pertimbangan utama di Departemen Hukum Internasional adalah kelowongan dosen untuk distribusi jumlah bimbingan. Mahasiswa juga mengisi “judul skripsi” di formulir ketika mendaftar konsentrasi, itu mungkin juga jadi pertimbangan kesekian tapi jelas bukan pertimbangan utama.
Perlu dipahami bahwa memang idealnya sebuah skripsi dibimbing oleh dosen yang memang berminat riset di bidang itu. Tapi, skripsi itu kan Cuma tingkat sarjana jadi tidak seurgen itu sebenarnya. Tingkat kedalaman kajiannya tidak sampai level disertasi yang memang segitunya perlu pengetahuan spesifik sub-bidang untuk membimbingnya. Jadi yang penting masih sesama bidang hukumnya (misalnya, sesama hukum pajak) insha Allah tidak masalah.
.
Pertanyaan Kedelapan: Bisa Ganti Pembimbing Skripsi?
Tidak semua pengalaman bimbingan skripsi itu enak. Ada beberapa pengalaman yang kurang enak, dan bahkan kadang ada yang sangat tidak enak sampai sulit melanjutkan penulisan skripsi. Atau, ada juga yang sebenarnya tidak masalah dengan DPS-nya, tapi ada dosen lain yang kamu lebih kepingin. Mekanisme pindah DPS bisa berbeda antar departemen, dan setidaknya akan ada dua poin: (a) persetujuan DPS lama, dan (b) persetujuan ketua departemen. Tapi, ada tiga nasehat saya terkait hal ini:
Nasehat pertama saya adalah untuk meminta nasehat dosen lain dan/atau kakak kelas (terutama yang pernah dibimbing oleh beliau). Bisa jadi masalahnya ada di kamu, atau jangan-jangan kesulitan-kesulitanmu adalah sesuatu yang sebenarnya wajar? Ini kalau ada masalah ya.
Nasehat kedua saya adalah memastikan dulu kondisi hubungan kalian dan konsekuensinya ke depan. Prinsipnya, ganti pembimbing itu sesuatu yang prosedural saja dan harusnya bukan hal yang membawa baper. Sayangnya, sebagian dosen akan mengambil hati betul kalau kalian minta pindah. Menurut saya sih harusnya nggak usah baper, tapi kalau berpegang pada ‘harusnya’ lalu kemudian langkah kalian di kelas konsentrasi terhambat, gimana?
Ini bukan berarti jangan pindah ya, tapi kalian harus bisa mengukur dampaknya. Di sini, sangat penting berkonsultasi dengan dosen lain yang se-departemen, untuk menanyakan bagaimana cara memitigasi dampak buruk yang mungkin terjadi (atau malah tidak ada masalah? Tergantung person masing-masing). Lebih bagus lagi kalau bisa konsultasi dengan dosen yang kamu mau jadikan DPS pengganti.
Nasehat ketiga, kalau memang akhirnya mau pindah, kulo nuwun dulu secara personal kepada DPS yang lama. Jangan tiba-tiba todong DPS lama minta tandatangan surat pindah departemen. Datangi secara personal dan minta tandatangan atau persetujuan di situ, sambil ngobrol basa basi lah. Ini masih relevan dengan poin kedua tadi.
.
Pertanyaan Kesembilan: Daftar Konsentrasi Hukum Internasional Disuruh Mengisi Judul Skripsi, Apakah Mengikat?
Kalau daftar konsentrasi Hukum Internasional, waktu daftar konsentrasi ada formulir yang harus kamu isi dan salah satu kolomnya adalah mengisi judul skripsi yang diinginkan.
Ternyata, menurut pengalaman, lumayan banyak mahasiswa yang galau mengisi ini. Panjang sekali bertapanya, karena begitu banyak yang dipikir. Maka saya sampaikeun di sini bahwa judul yang akan kalian isi di situ adalah TIDAK MENGIKAT. Mayoritas mahasiswa yang saya bombing, bahkan diri saya sendiri, akhirnya menulis skripsi yang beda sekali dengan draft yang awalnya saya tulis di formulir waktu daftar konsentrasi.
Alasannya sederhana: kalian baru mau masuk konsentrasi, belum mendapatkan matkul-matkul untuk mendalami konsentrasi kalian yang sangat mungkin kalian justru akan terinspirasi dan mendapatkan dasar-dasar untuk menulis skripsi kalian dari situ. Masa kita malah mengikat kalian pada sebuah judul sebelum kalian mempelajari semua itu?
Maka pertanyaannya: terus, ngapain dong ditanya di formulir? Jawabannya: sekadar untuk ancer-ancer awal saja buat kalian. Di pertanyaan ketujuh saya tulis bahwa judul ini mungkin menjadi pertimbangan bagi ketua departemen dalam memilihkan DPS untuk kalian, tapi ya belum tentu jadi pertimbangan dan kalaupun iya maka ya jadi pertimbangan nomor sekian. Jadi, intinya, nggak penting-penting amat.
Prakteknya, nanti kalian dalam menentukan judul skripsi akan diskusi dengan DPS. Pengalaman saya, mayoritas nggak pernah melihat lagi formulir yang kalian isi dulu itu. Jadi nggak usah pusing, diisi random juga nggak papa, atau ya sekedar menulis tema-tema umum yang kamu tertarik (misal “saya ingin menulis sesuatu tentang hukum ruang angkasa”) gitu aja nggak papa kok.
.
Pertanyaan Kesepuluh: Skripsi Itu Susah Nggak Sih?
Menurut saya pribadi, tidak. Tema dan judulnya kamu pilih sendiri, punya waktu satu semester (atau bahkan lebih, kalo se-betah itu dengan FH UGM. Susah-susah masuk UGM, kok cepet-cepet mau keluar sih? Haha) buat ngerjakan, ada dosen yang khusus membimbing kamu, enak banget toh? Coba kalo ini diterapkan di ujian mata kuliah lain, enak banget kan ya?
Cuma, kenyataannya kan ternyata nggak selalu semudah itu. Saya sendiri ngerjakan skripsi total hampir 3 bulan, karena ngerjakannya sambil malas-malasan plus sambil ngulang banyak banget matkul di semester itu. Bimbingan saya ada pula yang ngerjakan dua bulan. Tapi, ada juga yang sampe lebih setahun nggak selesai. Lantas gimana tuh?
Jawabnyaaa ya tergantung person masing-masing. Hanya saja, menulis skripsi itu beda banget dengan mata kuliah pada umumnya. Mungkin yang agak mirip adalah mata kuliah konsentrasi yang nilai akhirnya pake paper, itupun nggak se-sama itu. Jadi, kita belum punya pengalaman. Plus, jujur saja, pengalaman saya kuliah Metode Penelitian waktu S1 (dan saya curiga sampai sekarang masih sama), sangat tidak membantu. Matkul tersebut cuma ngajarin teknis formil bikin proposal, tapi nggak bener-bener mengajarkan secara mendalam apa itu penelitian dan bagaimana cara meneliti.
Kalau saya, dalam beberapa tahun belakangan punya pendekatan khusus terkait hal ini. Semua bimbingan saya yang baru akan saya kumpulkan lalu kita semacam ‘penyamaan persepsi’ tentang apa itu penelitian, bagaimana cara meneliti, dan khususnya bagaimana cara mendesain penelitian. Tapi nggak semua DPS melakukan ini sih.
Untuk bahas skripsi bisa bikin satu buku sendiri. Tapi berikut beberapa nasehat umum saya untuk melancarkan penulisan skripsi:
Pertama, kenalilah cara untuk mendesain penelitian, dan desainlah penelitianmu dengan baik dari awal. Kalau DPS nggak ngajarin, carilah cara untuk belajar. Teknologi udah maju kan hehe.
Kedua, untuk mendukung yang pertama, seawal mungkin kamu harus membentuk pola belajar yang tidak jauh dari riset. Bacalah artikel jurnal yang banyak untuk menunjang materi, jangan cuma belajar isinya tapi amati cara penulisnya mendesain penelitiannya (PS: mahasiswa emang harusnya banyak baca ya). Kalau bisa, ikutlah hibah-hibah penelitian yang ditawarkan kampus dan/atau menelitilah bersama dosen. Kalo gini, begitu mau nulis skripsi inshaAllah nggak seasing itu.
Ketiga, kenalilah dirimu sendiri dan bagaimana memicu performamu yang terbaik. Misalnya, ada yang lebih semangat kalo sambil multi-tasking, tapi ada juga yang lebih bisa kerja kalo fokus ke satu kerjaan saja. Yang terpenting juga di sini, know when you need help and know who to ask. Kenalilah kalo kamu mulai stressnya berlebih dan malah nyambung ke anxiety (kecemasan) dan butuh bantuan professional.
Keempat, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan DPS yang enak, karena mayoritas kasus kalian nggak banyak pilihan. Berkomunikasilah intensif dengan mereka, dan mintalah nasehat mereka kalau kamu ada masalah dalam pengerjaan skripsi.. Bagus juga untuk kalian riset ke senior atau dosen lain, gimana sih personal-nya DPS kalian? Apa yang kalian harus ketahui kalau dibimbing oleh beliau? Baca juga ini.
Kelima, pilihlah judul yang kamu memiliki passion tentangnya. Ini bukan hanya cliché semata, tapi passion yang benar akan melahirkan keinginan untuk mempelajari lebih dalam. Dan ini bukan bicara skripsi, tapi belajar secara umum. Ketika kalian kuliah di Fakultas Hukum, seharusnya kalian punya passion tertentu. Mungkin semester demi semester passion tersebut akan makin kuat, atau malah berubah, demikian pula ketika kalian memilih konsentrasi dan mengambil mata kuliah konsentrasi. Dan, ilmu itu TIDAK BOLEH hanya terbatas ruang kelas. Justru, idealnya ilmu itu mayoritasnya dari luar kelas. Bacalah, ikutilah diskusi, carilah expert atau komunitas untuk mendalami lebih lanjut, dan lain sebagainya. Itu namanya passion. Sehingga, ketika sampai pada saat kalian memilih judul skripsi, seharusnya tidak bermula dari titik nol kayak isi bensin.
Keenam, pilihlah judul yang sesuai kebutuhanmu. Passion itu ideal, tapi bukan syarat mutlak. Saya melihat ada trend berbeda-beda di mahasiswa yang menulis skripsi. Ada yang menulis sesuatu karena memang passion ingin memecahkan masalah tertentu yang dia sangat concern, ada yang flexing mau menunjukkan kebolehannya dalam mengkaji isu yang besar, ada yang cuma pengen lulus aja gak mau susah. Komunikasikan ini dengan DPS kalian, supaya sama-sama bisa tahu apa ekspektasinya dalam penulisan skripsi ini sesuai kemampuan dan sisa waktu yang kalian punya.
FYI “Cuma pengen lulus aja gak mau susah” ini bukan aib ya. Justru, salah satu bimbingan saya yang paling brilian malah skripsinya seperti itu. The thing is, hidup ini kan bukan buat skripsi aja ya. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Bisa aja sekian tahun di FH UGM, akhirnya merasa gak mau berkarir di bidang konsentrasinya (atau bahkan gak mau berkarir di bidang hukum) jadi Cuma sekadar mau lulus aja terus mau move on. Itu pilihan.
Ketujuh, skripsi bukan mahakarya. Skripsi memang mewakili apa yang kalian pelajari selama sekian tahun kuliah, mungkin bukan secara tema (karena judul skripsi kan spesifik banget, dibandingkan dengan sekian puluh mata kuliah yang kalian ambil) tapi secara pembentukan kompetensi dan wawasan seorang pelajar hukum. Tapi, at the end of the day, mau didramatisir seperti apapun juga, ini ‘cuma’ skripsi saja. Bukan Thesis, Disertasi, atau semisalnya. Bukannya saya mau bilang jangan dikerjakan dengan serius, justru kalian harus serius karena mau lulus kan ya?
Poin saya adalah, don’t be too hard on yourself. Tidak sedikit mahasiswa yang terlalu stress karena dia terlalu perfectionist. Mendapatkan gelar sarjana itu bukan akhir perjuangan, justru dia adalah awal perjalanan kalian.
.
Bonus Pesan Sponsor: Pamer Dikit Publikasi Mahasiswa Konsen Hukum Internasional
Satu fitur menarik dari konsentrasi hukum internasional adalah semangat publikasi di kalangan mahasiswa. Silahkan melihat daftar publikasi mahasiswa konsentrasi hukum internasional di bagian paling bawah pada halaman ini. Akan terlihat banyak sekali publikasi mahasiswa konsen di sana.
Kenapa banyak publikasi mahasiswa? Setidaknya ada tiga alasan:
Pertama, ada sebagian mata kuliah yang menjadikan penulisan paper atau opini tertulis sebagai tugas atau penilaian akhirnya. Rasanya sayang, mahasiswa sudah capek-capek berfikir keras berargumentasi tapi yang menikmati cuma dosennya dan satu atau dua temannya. Masyarakat pun berhak atas kontribusi ilmiah kita! Lagipula, akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa jika ia lulus bukan hanya dengan nilai baik tapi ada tambahan prestasi berupa publikasi di CV-nya, bukan?
Kedua, tentu ada di kalangan mahasiswa yang agak ambis sehingga banyak tulisan, bahkan kadang saling balas. Dan di sini saya tidak menggunakan kata itu secara negatif, karena ambisius –selama tidak melakukan hal yang tidak etis apalagi melawan hukum– adalah hal yang baik. Yang sangat negatif, dan ini betul terjadi, adalah ketika kalian yang “tidak ambis” mulai menjelek-jelekkan yang “ambis” sehingga orang jadi takut mau “ambis”. Akhirnya nggak jadi maju ke full potential. Sedangkan penulisan seperti ini bermula dari concern ketika ada kemunkaran terjadi di sekitar kita, yang tentu jadi amanah bagi orang-orang yang punya ilmu relevan.
Ketiga, mahasiswa konsen HI punya tradisi selama 4 tahun ini. Kadang ketika ada pejabat publik atau tokoh ngomong sesuatu yang relevan dengan hukum internasional yang menyesatkan masyarakat, mahasiswa kami maju untuk mengklarifikasi di media massa. Anggota DPR? Hajar. OPM? Hajar. Perdana Menteri Belanda? Hajar. Saya berharap tradisi ini bisa terus berjalan, atau bahkan terus meningkat.